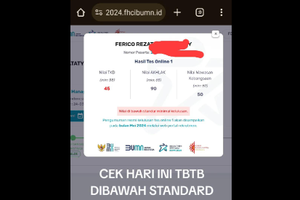Sumbu Filosofi Yogyakarta Ditetapkan Warisan Budaya UNESCO, Sultan: Mengandung Filosofi "Hamemayu Hayuning Bawana"

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Sumbu Filosofi Yogyakarta telah ditetapkan sebagai warisan budaya oleh UNESCO. Sumbu yang membentang dari Panggung Krapyak, Keraton Yogyakarta, hingga Tugu Pal Putih ini memiliki makna Hamemayu Hayuning Bawana.
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X menjelaskan bahwa awalnya, Pemerintah DIY kesulitan untuk menerjemahkan Hamemayu Hayuning Bawana ke bahasa asing. Karena, takut terjadi kesalahan jika diartikan dalam bahasa asing.
“Kita enggak tahu persis, takut keliru. Jadi itu hanya (diartikan) keindahan, kesejahteraan kan kira kira begitu. Untuk menjaga lingkungan kan gitu. Kita enggak berani menerjemahkan untuk tidak salah,” ujar Sultan saat ditemui di Kantor Gubernur DIY, Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Selasa (19/9/2023).
Baca juga: Mengenal Sumbu Filosofi Yogyakarta yang Resmi Diakui Warisan Budaya oleh UNESCO
Namun, setelah mengikuti proses dengan UNESCO barulah, UNESCO mendefinisikan Hamemayu Hayuning Bawana sebagai sustainable development. Sustainable development baru menjadi tujuan UNESCO pada 1990, sedangkan sikap sudah diterapkan oleh Keraton Yogyakarta sejak 1755.
“Kita baru mau memahamkan bahwa menjaga kelangsungan dunia ini lingkungan dengan segala isinya itu sustainable development ini kan baru PBB sendiri. Untuk goalnya baru tahun 1990-an. Ternyata Jogja kan sudah hamemayu diciptakan tahun 1755. Makanya di situ tidak hanya untuk Yogyakarta Indonesia, tapi juga untuk dunia,” jelas Sultan.
Sultan juga menjelaskan dengan sustainable development sebagai makna yang terkandung pada sumbu filosofi, maka dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat baik langsung maupun secara tidak langsung.
Lanjut dia, pembangunan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat tetap akan berjalan hanya saja, ada kontrol berupa lingkungan itu dibangun dengan baik dan tidak dilakukan perusakan saat pembangunan dilakukan.
“Tapi filosofinya kan tidak hanya batasnya itu (batas sumbu filosofi), seluruh DIY, bagaimana menjaga lingkungan itu tetap memberikan kehidupan pada manusia bukan merusak bumi ciptaannya,” kata dia.
Pembangunan yang dilakukan bakal turut memperhatikan lingkungan. Sultan mencontohkan, banjir tidak hanya disebabkan karena bencana alam tetapi juga adanya andil perusakan alam oleh manusia.
Baca juga: Jadi Warisan Dunia UNESCO, Ketahui 5 Fakta Sumbu Filosofi Yogyakarta
“Sustainable development kan tiap tahun dari sisi anggaran dari departemen selalu ada, makannya pemerintah juga ngoyo untuk green, untuk lingkungan ada, sama programnya untuk itu. Tapi dibatasi bagaimana lingkungan itu tetap terjaga,” jelas Ngarsa Dalem.
Sementara itu, dikutip dari laman resmi Keraton Yogyakarta menjelaskan sumbu filosofi dibangun oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I, yang pada saat itu dikenal sebagai Pangeran Mangkubumi, yang memulai membangun Kota Yogyakarta.
 Tugu Pal Putih atau Tugu Jogja, salah satu dari tiga titik Sumbu Filosofi Yogyakarta. Oleh UNESCO, kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta dimasukkan ke dalam Warisan Budaya Dunia.
Tugu Pal Putih atau Tugu Jogja, salah satu dari tiga titik Sumbu Filosofi Yogyakarta. Oleh UNESCO, kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta dimasukkan ke dalam Warisan Budaya Dunia.Pengejawantahan konsep ke dalam tata ruang Kota Yogyakarta dihasilkan dari proses menep, atau perjalanan hidup Pangeran Mangkubumi.
Dilahirkan sebagai putra Raja Mataram Sunan Amangkurat IV, Pangeran Mangkubumi tumbuh besar di lingkungan Keraton Kartasura. Karena perpindahan lokasi istana, berikutnya Pangeran Mangkubumi mengetahui persis seluk beluk Keraton Surakarta.
Keraton Yogyakarta dibangun berdasarkan konsepsi Jawa dengan mengacu pada bentang alam yang ada, seperti gunung, laut, sungai, serta daratan. Prinsip utama yang dijadikan dasar pembangunan keraton oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I adalah konsepsi Hamemayu Hayuning Bawana.
Artinya membuat bawana (alam) menjadi hayu (indah) dan rahayu (selamat dan lestari). Konsep-konsep tersebut diejawantahkan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I dengan Laut Selatan dan Gunung Merapi sebagai poros.
Baca juga: Apa Itu Sumbu Filosofi Yogyakarta yang Diusulkan Jadi Warisan Budaya Tak Benda UNESCO?
Perjalanan dari Panggung Krapyak menuju keraton mewakili konsepsi sangkan (asal) dan proses pendewasaan manusia. Sementara perjalanan dari Tugu Golong Gilig menuju ke keraton mewakili filosofi paran (tujuan). Yaitu perjalanan manusia menuju Penciptanya.
Panggung Krapyak terletak kurang lebih 2 km dari Keraton Yogyakarta. Berbentuk segi empat dengan tinggi kira-kira 10 meter, lebar 13 meter, dan panjang 13 meter.
Panggung Krapyak terdiri dari dua lantai yang dahulu dihubungkan dengan tangga kayu. Lantai atas berupa ruang terbuka berpagar. Bangunan ini dahulu digunakan oleh Sultan untuk menyaksikan prajurit atau kerabatnya dalam berburu (ngrapyak) rusa.
Secara simbolis, Panggung Krapyak memiliki makna awal kelahiran atau rahim. Ini ditegaskan dengan keberadaan kampung di sebelah barat laut bernama Mijen, yang berasal dari kata “wiji” (benih).
Pohon asem atau asam (Tamarindus indica) dan pohon tanjung (Mimusops elengi) yang ditanam sepanjang jalan dari Panggung Krapyak menuju keraton juga memiliki arti tersendiri. Sinom, daun asam, melambangkan anom (muda). Bersama dengan pohon tanjung melambangkan anak muda yang selalu disanjung-sanjung oleh lingkungannya.
Lebih ke utara lagi terdapat Alun-Alun Selatan yang sekitarnya ditanami pohon pakel dan kweni. Pohon-pohon ini melambangkan pemuda yang sudah akil balig dan sudah wani (berani) meminang gadis pujaannya.
Lebih ke utara, terdapat Siti…
-
![]()
Sumbu Filosofi Yogyakarta Diusulkan sebagai Warisan Dunia, UNESCO Lakukan Pengecekan
-
![]()
Mengenal Sumbu Filosofi Yogyakarta, Konsep Tata Ruang Peninggalan Sri Sultan Hamengku Buwono I
-
![]()
Hubungan 3 Bangunan di Sumbu Filosofi Yogyakarta, Apa Maknanya?
-
![]()
Sumbu Filosofi Diusulkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda UNESCO, Malioboro Dicanangkan Jadi Kawasan Rendah Emisi
-
![]()
Mengenal Sumbu Filosofi Yogyakarta yang Resmi Diakui Warisan Budaya oleh UNESCO